Anda juga terkecoh ya? Saya tak sedang membicarakan aspek naratif dari Atomic Blonde (meski memang ada kej... oke, saya takkan membahasnya). Maksud saya adalah bagaimana film ini ternyata menjadi film yang berbeda dari apa yang digembar-gemborkan oleh materi promonya. Anda tahu, film ini digarap oleh mantan sutradara John Wick. Trailer menggiring kita percaya bahwa Atomic Blonde adalah film yang hanya soal aksi brutal dengan koreografi keren yang diwarnai estetika visual unik. Itu betul juga sebenarnya, tapi saya juga tak menduga bahwa plotnya lebih berfokus pada dinamika dunia spionase dengan segala intrik dan metode tipu-tipunya. Secara naratif, ia mengingatkan pada thriller spionase lawas. Plotnya njelimet. Atomic Blonde adalah semacam film mata-mata dengan penceritaan ala Tinker Tailor Soldier Spy ditambah bumbu aksi hiperkinetik ala John Wick.
Atomic Blonde menjadi wadah bagi persona tukang tonjok, tendang, tusuk, dan tembak dari Charlize Theron, yang sebelumnya sudah membuktikan bahwa ia bisa menjadi bintang film aksi yang tangguh lewat Mad Max: Fury Road (jangan biarkan saya membahas Aeon Flux). Theron bermain sebagai agen khusus bernama Lorraine. Film ini mengakomodasinya untuk menampilkan beberapa stunt berbahaya, memakai pakaian glamor, dan, uhm, bercumbu dengan wanita, meski yang terakhir takkan kita lihat terlalu banyak karena kita menontonnya di bioskop Indonesia. Terima kasih LSF.
Setting-nya adalah di tahun 1989, beberapa saat sebelum Tembok Berlin dirubuhkan. Namun ini bukan tentang hal tersebut, begitu klaim filmnya. Saya ingin membuat argumen bahwa jika setting-nya diganti, film ini takkan sedemikian efektif. Latar belakang peristiwa politik penting dimana kecurigaan tereskalasi dan warga banyak demo turun ke jalan ini memberikan ketegangan tersendiri. Mata-mata dari pihak Barat dan Timur harus dan sedang mempersiapkan metode masing-masing untuk bermain di dunia baru pasca Perang Dingin. Informasi adalah senjata. Anda sekarang mungkin mulai berpikir, saya ini bicara apa; apa hubungannya film tonjok-tonjokan dengan obrolan sejarah. Namun percayalah; ini menjadi hal yang esensial bagi motif salah satu karakter di akhir.
Garis besar plotnya sudah sering kita lihat di film mata-mata manapun. Pasca kematian salah satu agennya, agensi rahasia Inggris, MI6 mengutus Lorraine ke Berlin untuk merebut kembali “The List”, daftar nama semua agen mata-mata yang masih aktif. Agen yang tewas tersebut dibantai oleh agen KGB-nya Rusia, dan sekarang ia berencana menjualnya kepada penawar tertinggi. Misi kedua Lorraine adalah menangkap/mengeksekusi agen ganda berjuluk Satchel yang berkhianat dan kemungkinan ada hubungannya dengan “The List”.
Belum lima menit sampai di Berlin, Lorraine terpaksa harus mengorbankan high heels-nya untuk mengatasi orang yang menjebaknya. Baru kemudian Lorraine bertemu dengan partnernya, Percival (James McAvoy), agen Inggris yang sudah begitu dalam menyamar sampai terlihat meyakinkan sebagai preman jalanan di Berlin. Ia mungkin juga punya agenda tersendiri yang patut dipertanyakan. Percival punya kontak dengan nama-kode Spyglass (Eddie Marsan), yang katanya hafal semua isi “The List”, luar kepala. Saran dari atasan Lorraine: “Jangan percaya siapapun”, tapi bagaimana dengan Delphine (Sophia Boutella), agen Prancis polos yang tampaknya tulus mendekatinya?
Cara filmnya memplotkan cerita kadang membuat kepala pusing, terutama jika anda berusaha untuk menyusunnya secara kronologis. Film ini, yang diadaptasi dari novel grafis berjudul The Coldest City karya Antony Johnston dan Sam Hart, menggunakan mekanisme flashback. Sebagian besar merupakan cerita Lorraine yang sedang diinterogasi oleh atasannya di MI6 (Toby Jones) dan wakil dari CIA (John Goodman) demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam 10 hari terakhir. Penulis skripnya bisa membuat alasan dengan bilang bahwa semua cerita ini adalah fragmen dari ingatan Lorraine. Ia tak harus tersusun secara berurutan.
Atomic Blonde punya atmosfer retro, namun bukan retro-lawas melainkan lebih ke retro-keren. Pembuat filmnya menekankan visual yang dingin dengan menggunakan palet warna neon berskema merah-biru. Geberan lagu lama yang keren mengiringi hampir setiap sekuens aksi, mulai dari New Order, Depeche Mode, The Clash, David Bowie, sampai George Michael.
Sutradaranya adalah David Leitch, yang pernah menangani John Wick sebelum berpisah dengan rekannya, Chad Stahelski di John Wick 2. Pengalamannya sebagai stuntman veteran tercermin dari sajian sekuens aksinya yang tanpa tedeng aling-aling. Klimaksnya adalah adegan pertarungan brutal dalam apartemen yang (kelihatannya) disorot dalam satu take tanpa terputus selama hampir 10 menit. Lorraine menghajar dan dihajar tanpa henti dari atas hingga ke bawah tangga, masuk ke dalam kamar, keluar dari pintu utama, sampai kabur dengan mobil di jalanan. Terlalu banyak sekuens aksi di dalam film lain yang direkayasa dengan gerakan kamera hiperaktif, tapi disini semua tampak spontan. Kamera menempel menyorot Theron dari dekat, sementara yang kita dengar hanyalah suara tulang patah, tubuh tertusuk, dan napas tersengal. Hal menarik saat mendapati bahwa Lorraine tak selalu ditampilkan elegan sebagaimana karakter mata-mata generik lain. Saat selesai dihajar, tubuhnya memar, wajahnya bengkak.
Performa fisik yang dipersembahkan oleh Theron luar biasa. Sama seperti yang dilakukan Keanu Reeves untuk John Wick, Theron melakukan sebagian besar aksi stunt-nya sendiri. Tak hanya karismatik sebagai agen wanita yang kompeten dalam aksi spionase, ia juga meyakinkan saat mengayunkan wajan, menghajar pria-pria besar. Ada satu adegan di hotel dimana karakter Lorraine memasang penutup muka, siap beraksi, dan disini saya berpikir, “Ah trik murahan, pasti biar tak kentara saat Theron diganti stuntman”. Tapi saya keliru. Tanpa sorotan terputus, Lorraine mengalahkan mereka, dan saat membuka penutup mukanya, I’m like, “Damn, woman”.
Menurut saya, judul aslinya The ((Coldest)) City sebenarnya lebih cocok dibanding ((Atomic)) Blonde yang terkesan relatif meledak-ledak, karena secara emosional filmnya dingin. Tak ada percikan yang benar-benar memancing empati. Namun, saya punya dugaan sendiri. Mungkin ini karena filmnya diceritakan dari sudut pandang Lorraine yang memang dingin. Kita tak begitu mengetahui masa lalu Lorraine, dan hanya sedikit mengintip sisi kemanusiaannya, karena bagi Lorraine, pada akhirnya yang penting hanyalah misinya.
Anda telah membaca artikel tentang Atomic Blonde (2017) ~ Review Movie dan anda juga bisa menemukan artikel Atomic Blonde (2017) ~ Review Movie ini dengan url http://moviemoviemaniac.blogspot.com/2017/08/atomic-blonde-2017-review-movie.html. Anda boleh menyebarluaskan atau mengcopy artikel Atomic Blonde (2017) ~ Review Movie ini jika memang bermanfaat bagi Anda, namun dengan catatan jangan lupa untuk mencantumkan link sumbernya.
Artikel Terkait


 11.58
11.58
 Movie Mania
Movie Mania


 Posted in:
Posted in: 

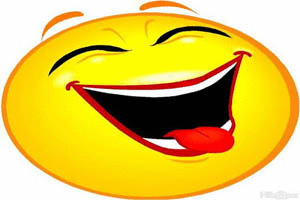



0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentarlah dengan baik...